Ketika Cinta Guru Meredup dan Upaya Menghidupkannya Kembali
Ada masa ketika seorang guru berdiri di depan kelas dengan tubuh yang hadir, tetapi hatinya tidak sepenuhnya berada di sana. Kata-katanya mengalir, namun tidak lagi mengandung getaran kasih. Tugasnya terselesaikan, tetapi tanpa rasa bangga dan tanpa aliran makna. Itulah masa ketika guru mengalami defisit cinta dan welas asih—sebuah kondisi yang sesungguhnya sunyi, tetapi berjejak dalam segala sisi pembelajaran.
Guru bukan makhluk tanpa batas. Mereka pun memiliki keteduhan yang bisa retak, energi yang bisa habis, dan semangat yang bisa redup. Rutinitas yang menekan, target administrasi yang menumpuk, kurangnya penghargaan, serta ruang kerja yang dingin perlahan mengikis ketulusan dan kelembutan yang dulu menjadi alasan mereka memilih dunia pendidikan. Mereka berjalan, tetapi letih; mengajar, tetapi tanpa rasa; mendampingi, tetapi tanpa getaran kasih.
Padahal, pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan. Ia adalah seni menghadirkan kehangatan, membangunkan potensi, dan menyalakan harapan. Pendidikan lahir dari hati yang penuh cinta. Ketika cinta itu retak, relasi guru dan peserta didik kehilangan keindahannya. Teguran menjadi lebih keras, sabar menjadi lebih tipis, dan kelas berubah menjadi ruang yang kaku. Anak-anak belajar, tetapi tidak tumbuh dalam kasih. Guru mengajar, tetapi tidak tumbuh dalam makna.
Namun cinta tidak pernah benar-benar mati; ia hanya tertimbun oleh debu kelelahan. Ketika guru berhenti sejenak untuk menyadari betapa berharganya tugasnya, cinta itu mulai terangkat kembali ke permukaan. Ketika mereka diberi ruang untuk bernafas, didengar keluhannya, diapresiasi perannya, dan disapa dengan tulus oleh pimpinan sekolah, bibit-bibit welas asih itu kembali tumbuh. Ketika sesama guru saling menguatkan, bukan saling menghakimi, ruang sekolah dipenuhi energi positif yang menular.
Pemulihan cinta dimulai dari hal-hal kecil: senyuman yang tulus, doa yang diucapkan bersama, sapaan lembut kepada siswa, dan kesediaan memaafkan diri sendiri atas segala keterbatasan. Guru perlahan kembali menemukan bahwa profesi ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi ibadah yang memancarkan pahala. Bahwa setiap kesabaran adalah kebaikan yang dicatat oleh Allah. Bahwa setiap anak yang disentuh hatinya akan membawa jejak kebaikan sampai jauh di masa depan.
Ketika cinta kembali menyala, kelas berubah. Suasana menjadi lebih teduh. Siswa merasa dihargai, bukan dihakimi. Guru mengajar dengan jiwa, bukan sekadar prosedur. Lingkungan sekolah menjadi ekosistem yang penuh rahmah—tempat semua pihak saling menjaga dan saling memanusiakan.
Narasi ini mengingatkan kita bahwa guru tidak hanya membutuhkan pelatihan dan perangkat ajar, tetapi juga ruang untuk disayangi. Mereka tidak hanya dituntut untuk kuat, tetapi juga berhak dirawat. Karena cinta guru adalah cahaya peradaban. Bila cahaya itu meredup, generasi ikut meraba-raba. Namun bila cahaya itu menyala kembali, maka sekolah menjadi rumah bagi tumbuhnya manusia-manusia yang penuh kemuliaan.
Pada akhirnya, cinta adalah sumber segala pembelajaran. Dan tugas kita bersama adalah memastikan bahwa cinta itu terus hidup—di hati para guru, di ruang-ruang kelas, dan di seluruh ekosistem pendidikan yang ingin menanamkan welas asih sebagai landasan masa depan.
*renungan sederhana_maraknya workshop_belum mampu menghadirkan layanan kualitas pembelajaran*


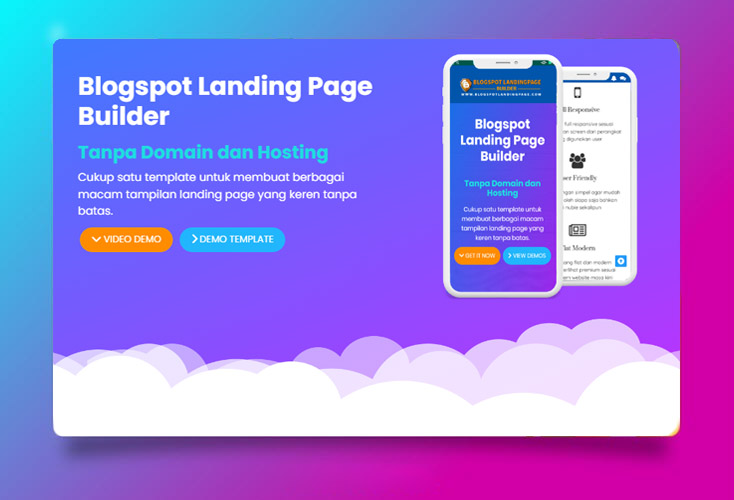




Tidak ada komentar:
Posting Komentar